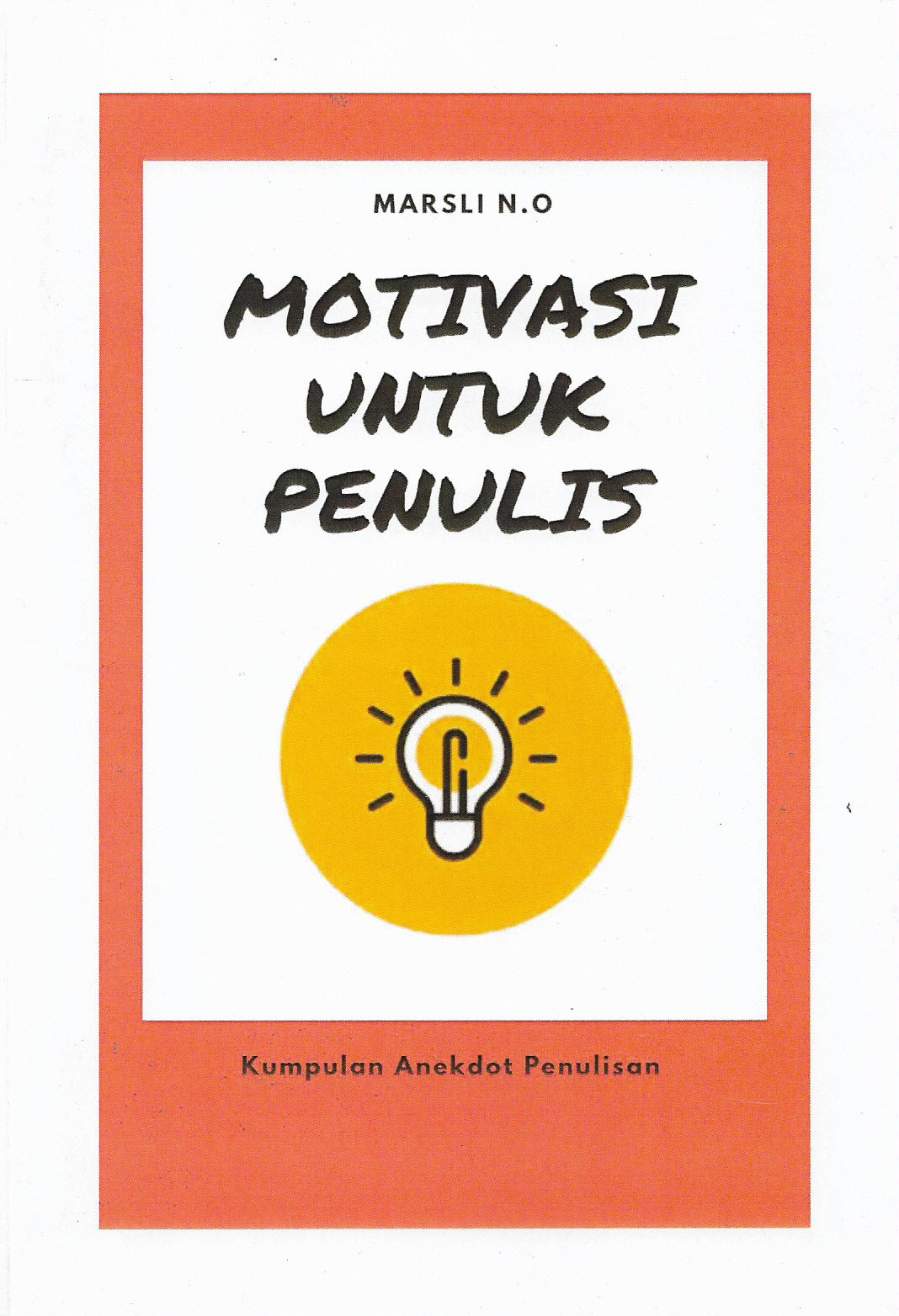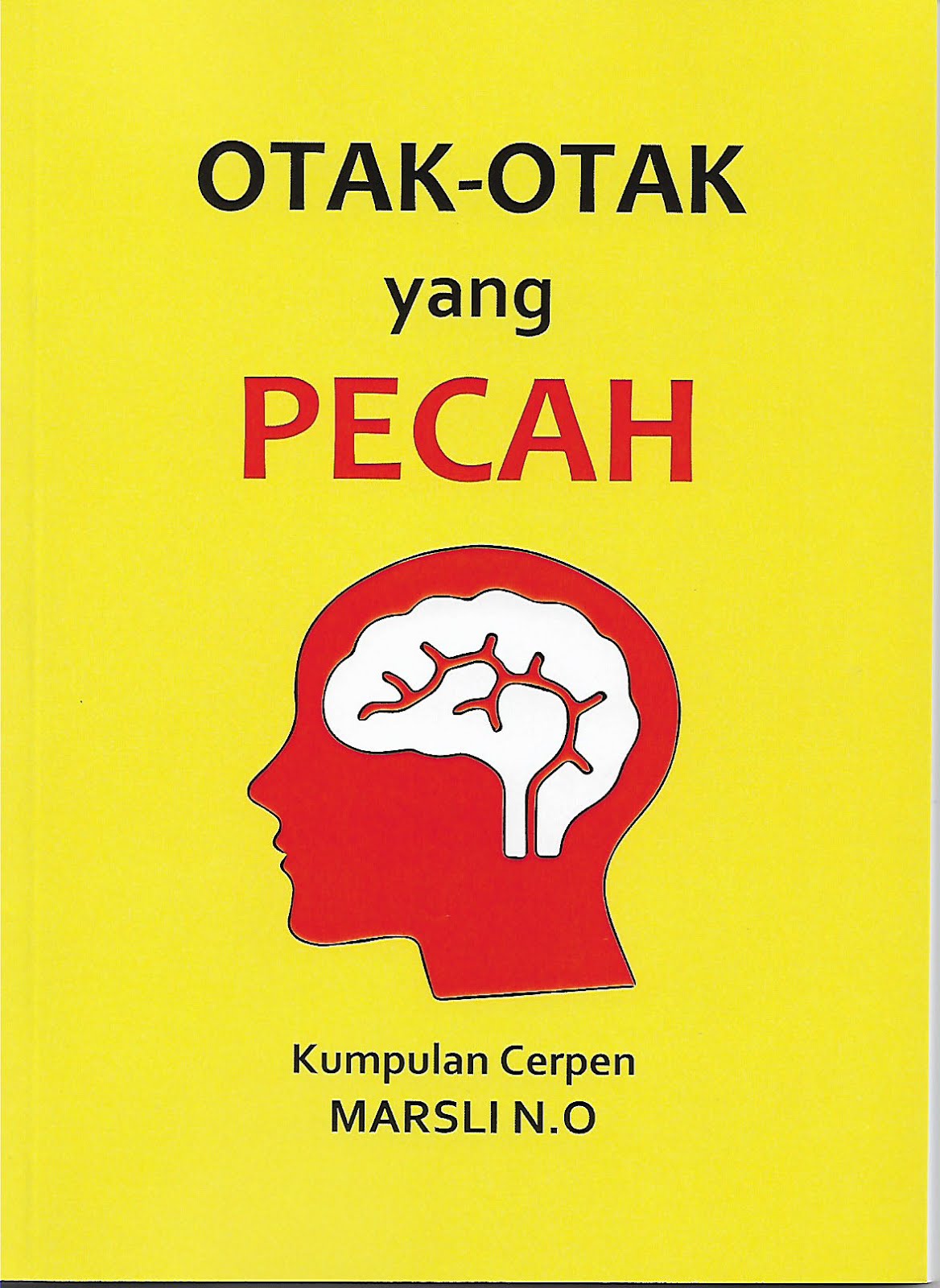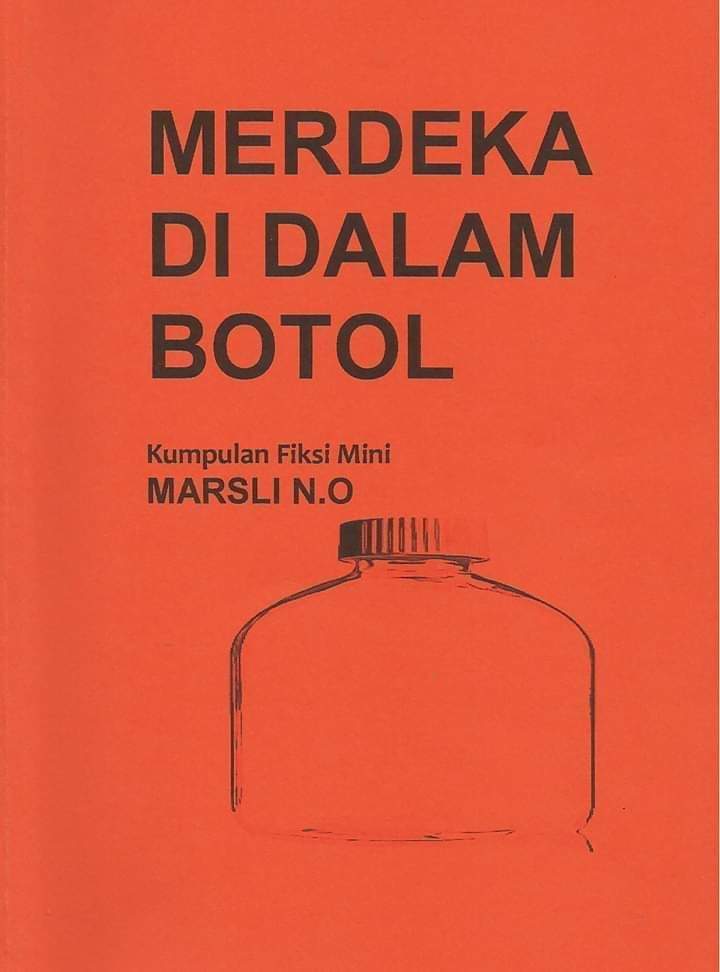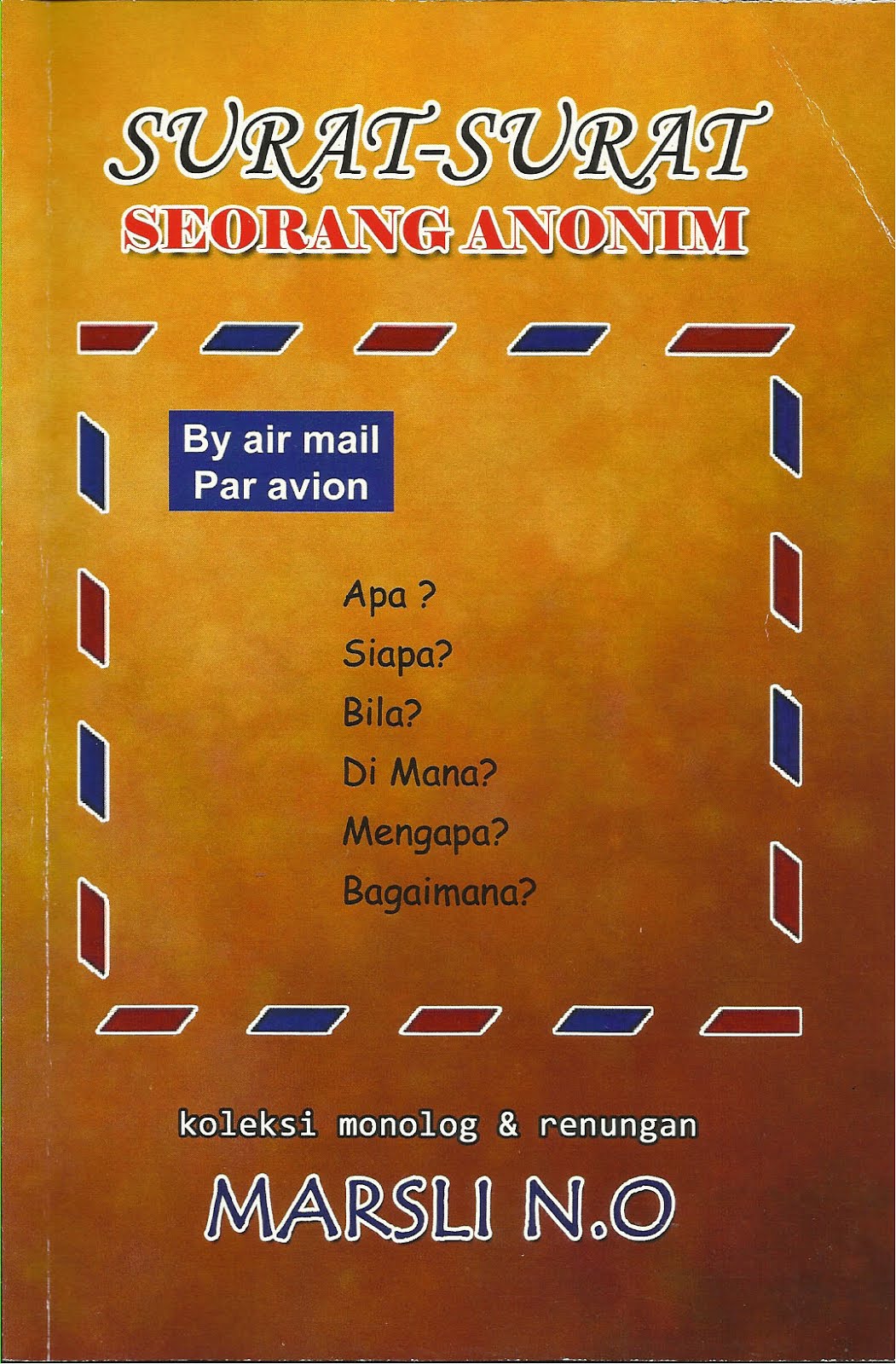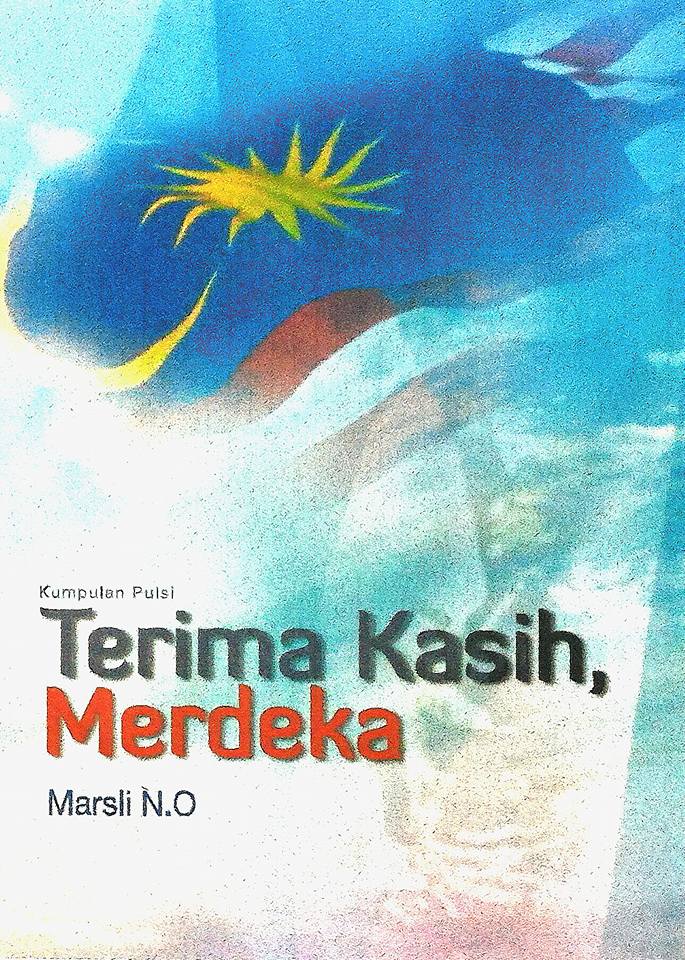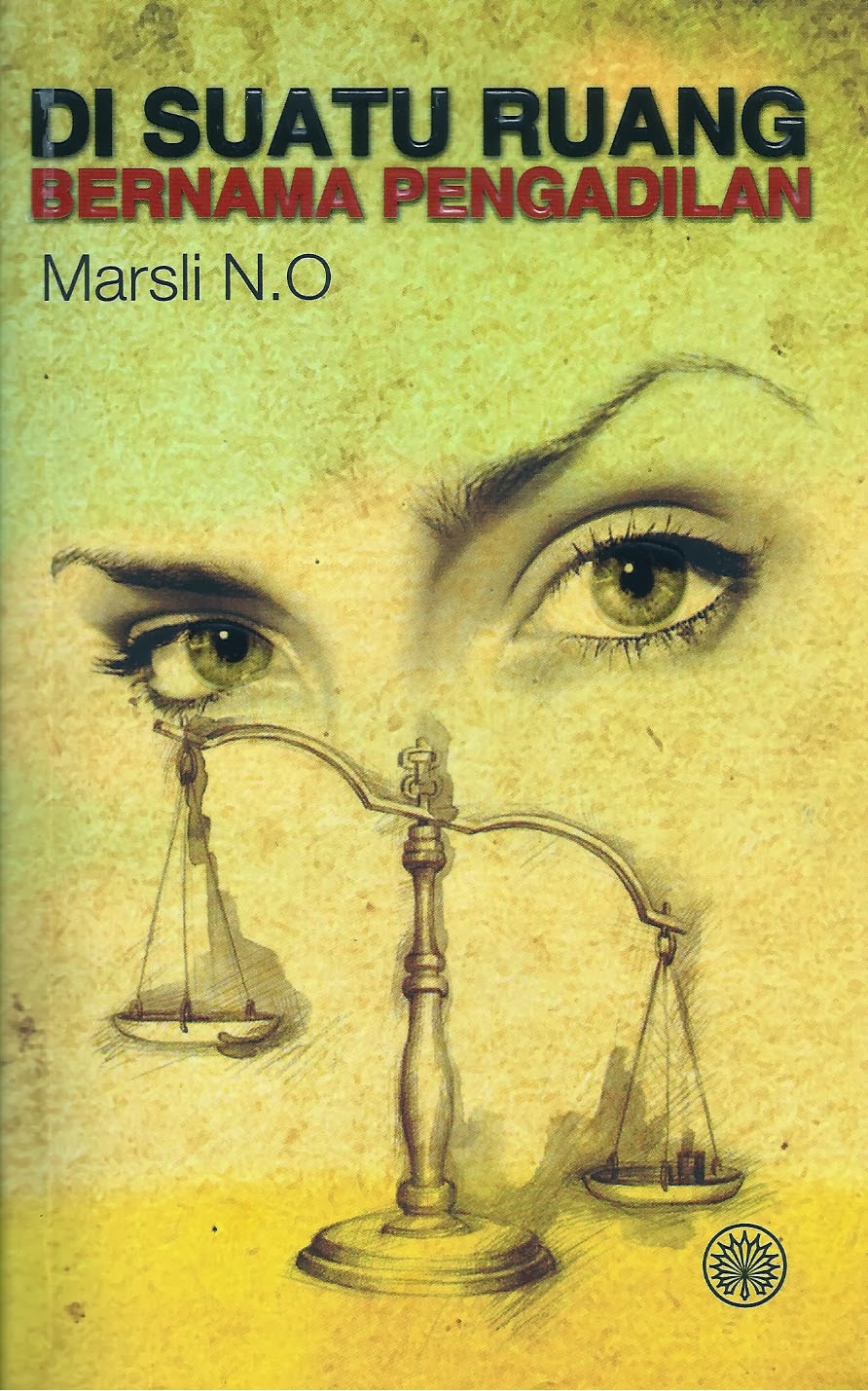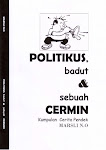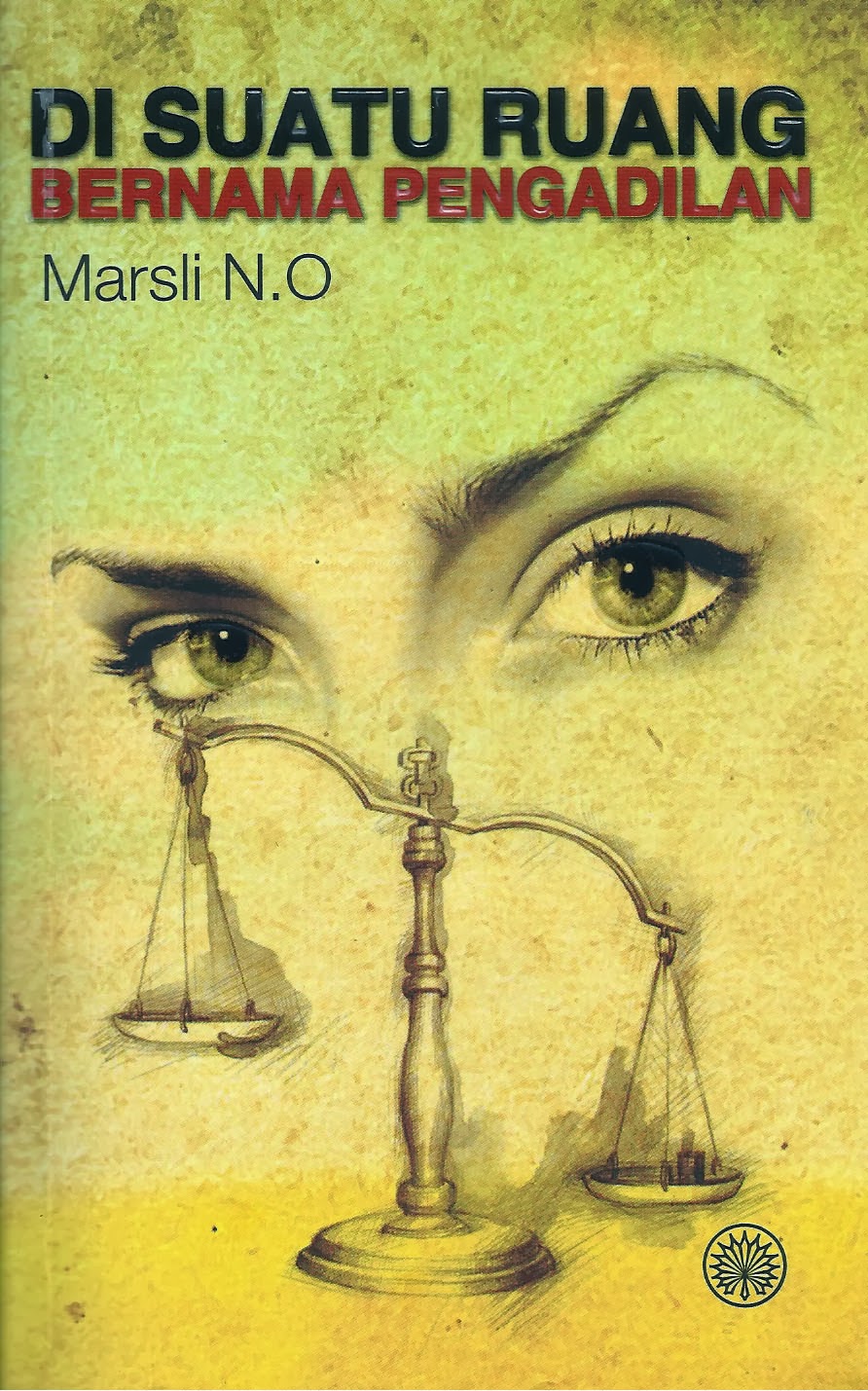Jumaat, Januari 25, 2013
SI CERDIK YANG TOLOL
TENTULAH dia berasa dan berfikir betapa lebih cerdiknya dia berbanding orang lain yang tidak ke mana-mana itu. Tentulah bertambah-tambah lagi dia berasa betapa dirinya berlebih cerdiknya itu berbanding orang lain yang tidak ke mana-mana itu kerana dapat mencari-cari kebodohan orang lain yang berkenaan dalam beberapa tulisannya dan dengan penuh bangga diri maka didedahkan di dalam beberapa siri tulisannya.
Dia sebenarnya lupa atau sengaja buat-buat lupa. Orang yang dia bukakan kebodohannya itu sebenarnya memang pun seorang yang boleh dianggap bodoh dan sebagai orang yang lebih cerdik, sepatutnya dialah yang tolong membantu mengajar dan menunjukkan kesilapan orang yang bodoh itu dengan cara yang lebih berhemah supaya orang yang memang pun bodoh itu tidak terus berada di dalam keadaan bodohnya.
Tetapi bukan itu yang berlaku. Dia sebaliknya lebih gembira dan berasa bangga kerana dapat membuka dan menunjukkan kebodohan orang yang memang bodoh itu di dalam sejumlah tulisannya. Tentunya dengan hujah-hujah ilmu akademik yang memang dipelajarinya.
Malah, tanpa sedikit pun rasa aib dan malu, tatkala tulisan-tulisannya yang membukakan secara terbuka kebodohan seorang yang memang bodoh itu dibukukan, dia dengan bertambah-tambah bangganya menayangkan buku yang memuatkan juga tulisannya yang sedemikian rupa itu ke mana-mana.
Bagi dia, dia sudah berjaya sebagai seorang yang cerdik dan wajar berbangga kerana sudah memiliki buku. Walaupun buku itu hanyalah berupa kumpulan beberapa tulisannya yang terpencar-pencar di sana sini sebelum ini dan bukan pun sebuah buku kajian mengenai sesuatu mauduk secara utuh.
Atau kalau pun ada penerbitan sebuah buku yang lain, judul atau mauduknya tidak lain merupakan peniruan terhadap suatu mauduk yang sudah pun dikaji dan diteliti oleh orang yang lain sebelumnya. Namun tetaplah dia tanpa rasa aib dan malu, berbangga-bangga dengannya.
Jadi begitulah. Dia yang mengaku dan berasa dirinya cerdik itu pun sebenarnya tetaplah ada bodohnya.
Misalnya, untuk menyatakan secara generalisasi mengenai sesuatu bukan sepatutnya dilakukan oleh orang yang terlebih cerdik seperti dia. Patutnya, mestilah ada hujah dan kajiannya. Selepas dikaji dan ditunjukkan data sebagai bukti, barulah ada hujahan dan dinyatakan sebagai dapatan. Dengan begitu, barulah ada otentiknya, barulah ada wibawanya.
Ini tidak. Kalau setakat menyatakan betapa kurangnya ayam di abad 21 ini bertelor kerana memakan dedak padi, tanpa data dan dapatan kajian, budak yang tidak masuk sekolah tinggi pun boleh bercakap dan berkata.
Ingat, sebagaimana yang awak akui dan jaja ke sana dan ke mari, awak adalah ahli akademik. Jadi, tidak malukah ahli akademik menulis dan bercakap sesuka hati sahaja tanpa sebarang bukti?
Atau, awak sebenarnya tidak lebih hanyalah si cerdik yang tolol?
Januari 25, 2013
Ahad, Januari 20, 2013
MENIKMATI PUISI SI DARWIS RIDZUAN HARUN
Oleh MARSLI N.O
marslino@yahoo.com
Buku Si Darwis
Pengarang Ridzuan
Harun
Penerbit Institut Terjemahan & Buku Malaysia
RIDZUAN HARUN atau nama penuhnya Mohd Ridzuan Harun lahir
1 Jun 1975 di Kebun 500, Pokok Sena,
Kedah. Pendidikan awalnya di Sekolah Kebangsaan Haji Idris, Tajar, Kedah.
Tahun 1988 hingga 1992 Ridzuan mendapat pendidikan
menengah di Sekolah Menengah Jabi, Pokok Sena sehingga Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) dan dari tahun 1993 hingga 1994 belajar di Sekolah Menengah Dato' Syed Omar, Alor Setar sehingga
STPM. Namun begitu, Ridzuan gagal
memperolehi sijil penuh.
Kegagalan itu tidak mematahkan semangat Ridzuan.
Percubaannya kali kedua menerusi sekolah swasta pada tahun 1996 telah berjaya
dan beliau berhasil menggenggam segulung sijil penuh STPM.
Dengan sijil penuh STPM itulah yang kemudiannya
melayakkan Ridzuan melanjutkan pengajiannya ke Universiti Putra Malaysia (UPM)
dari tahun 1997 hingga 2000 di bidang
Bacelor Sastera (Pengkhususan Bahasa dan Linguistik Melayu) dan kini
beliau sedang menyambung pengajiannnya ke peringkat sarjana di universiti yang
sama.
Tetapi sebagai penyair, dari manakah sebenarnya Ridzuan
Harun bertolak dan bermula? Selepas tampil dengan antologi puisi pertamanya
“Suluk Cinta” yang diterbitkan oleh
Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2008, tahun 2012 ini Ridzuan Harun tampil
lagi dengan antologi puisi kedua beliau ”Buku Si Darwis” yang diterbitkan
Institut Terjermahan dan Buku Malaysia.
Dalam pengantar buku puisi terbarunya ini, yang dijuduli sebagai
“Catatan Si Darwis Puisi”, Ridzuan Harun mengakui betapa beliau memilih ruang
dan jalan yang payah untuk mencintai puisi..
Bagi Ridzuan
Harun, menulis puisi bukan suatu kerja mudah. Namun begitu, beliau tetap
percaya dan sepenuhnya meyakini betapa: “Penyair harus berdiri di hadapan
bangsa, di hadapan zamannya – menjadi perenung, pencatat, menjadi cermin nusa;
bahkan menjadi “pengingat”.
Untuk dan kerana itulah melalui antologi yang memuatkan
50 puisi hasil cipta beliau sekitar tahun 2006 hingga 2011 ini Ridzuan Harun menampilkan puisi-puisi yang
sebahagian besarnya memaparkan gelodak resah dan gelora yang sesekali keras
mendebur pantai emosi kepenyairannya bila berhadapan dengan persoalan maruah
bangsa, bahasa dan madsa depan negaranya.
Malah sikap dan tegasnya pendirian Ridzuan Harun sebagai penyair yang diakuinya sebagai perlu
memikul peran sebagai “pengingat” ini ketara dinyatakan melalui susun atur
puisi-puisinya di dalam antologi ini, dengan mengawalinya melalui puisi
berjudul “Di Bawah Bulan Berwarna Emas Kudoakan Kau Sejahtera Selalu, Bahasaku”
sebagai puisi pertama mendepani pembaca.
Melalui puisi ini, Ridzuan Harun menyatakannya melalui
simbol betapa bahasa adalah:
kunang-kunang, sumbu, kandil, pelita, lentera, dian, suluh dan matahari,
yang sentiasa didoakan agar sejahtera sentiasa.
Memang jika dibaca secara permukaan atau apa yang
tersirat, puisi ini tidak lebih sekadar sebuah puisi berisikan doa dan harapan
daripada seorang penyair Melayu agar
bahasa miliknya sentiasa sejahtera.
Tetapi lantaran apakah yang mendorong doa dan harapan itu
dilontarkan penyair di dalam puisinya ini? Apakah ini berarti bahasa Melayu
sedang diancam oleh sesuatu sehingga wujud kebimbangan di hati penyair dan
mendorong puisi ini dizahirkan?
Secara tersirat dan tidak langsung Ridzuan Harun, dengan
menggunakan objek-objek sebagai pembanding dan simbol, ingin menyatakan betapa bahasa Melayu
mempunyai kekuatannnya yang teramat hebat. Namun kepekaan mata batinnya sebagai
seorang penyair, yang melihat dan
meneliti apa yang sedang dan sudah
melanda bahasa Melayu, mendorong Ridzuan
melahirkan rasa bimbangnya secara tidak
langsung melalui doa dan harapan.
Tidak hanya soal bahasa yang menjadi titik tolak
kebimbangan Ridzuan Harun. Persoalan politik bangsa dan negara juga turut
menenerjah sensitiviti kepenyairan Ridzuan.
Di dalam antologi ini, puisi-puisinya seperti “Politik
Malaysia, 2009” di halaman 19, “Aduhai Tanah Air” (20), dan serial sajaknya di
bawah judul “Sifir Politik” dengan jelas menyerlahkan pendirian Ridzuan yang
mempercaya betapa penyair: “.... harus berdiri di hadapan bangsa, di hadapan
zamannya – menjadi perenung, pencatat, menjadi cermin nusa; bahkan menjadi
“pengingat”.
Sebagai pemerhati, perhatian Ridzuan di dalam puisinya
“Politik Malaysia, 2009” jelas tertumpu kepada situasi di tahun 2009, yang
dinyatakannya sebagai: “...terasa kita sedang menangisi demokrasi tercalar/
atau terasa kita/ sedang mentertawakan demokrasi.”
Namun begitu, Ridzuan
Harun di dalam puisinya ini tidak meletakkan diri di pososi penghukum
atau pengikut buta seperti mana-mana kelompok yang sentiasa ingin memenangkan
kelompoknya semata-mata. Ridzuan sebaliknya memilih untuk menjadi lebih terbuka
dan kembali kepada hakikat diri kemanusiannya dengan melontarkan tanya kepada
Sang Maha Pencipta dengan tanya: “Tuhan, iktibar apakah ini?”
Atau dalam puisinya “Aduhai Tanah Air”, Ridzuan melihat
dan menyatakan rasa bimbangnya bila melihat pertelingkahan yang terjadi di
antara sesama, baik politikus mahupun agamawan, yang menurut hemat Ridzuan
tidak lain kerana: “...kerana sebidang kuasa/ dan sebaris penghormatan yang
dikejar.”
Peristiwa sosial seperti kehilangan adik Sharlinei,
kehilangan Pulau Batu Putih, pemergian Zubir Ali turut tidak lepas dari mata
perhatian Ridzuan.
Ridzuan juga tidak melupakan untuk menyatakan sesuatu
mengenai penyair yang dikaguminya, T. Alias Taib dalam puisinya “Puisi Adalah
Peta Perjalanan Hidupnya”. Menurut hemat Ridzuan, segala khazanah puisi yang
ditinggalkan oleh T. Alias Taib melayakkannya diibaratkan sebagai “... songket
berkilau/ dari jauh pun tampak sinar dan serinya.”
Perjalanan dan kunjungan juga turut menyentuh sensitiviti
kepenyairannya, yang diutarakan antaranya melalui puisi “Percakapan Kepada
Mudsi (iii)” di halaman 14, “Tanjung Rhu, Petang Runduk (41)”, “Catatan di
Beting Pasir” (43) dan “Tanjung Rhu,
Lewat Malam” (44).
Antologi puisi “Buku Si Darwis” buah tangan penyair
Ridzuan Harun dapat ditanggap sebagai sebuah pengukuhan pengakuan seorang
penyair yang kian menampakkan sosok keperibadian kepenyairannya.
Justeru itu jugalah, Ridzuan tidak lupa menurunkan
sejumlah puisi bersifat renungan dan rekrospektif dirinya, seperti di dalam
puisi”Belajar Menjadi Rama-Rama dan Merpati” di halaman 56, “Memilih Diam”
(57), “Sebahagian Autobiografi” (58), “Kepada Ridzuan” (63), “Darwis” (64) dan
“Buku Si Darwis” (65).
Ternyata, melalui antologi puisi keduanya ini Ridzuan
sudah cukup bersiap sedia dengan penampilan puisi-puisinya. Dengan kesedarannya
sebagai “darwis puisi”, Ridzuan menyedari dan insaf akan kehadiran dirinya.
Ridzuan harun bukan seluruhnya seorang darwis, tetapi sudah mulai berjalan dan
menuju ke arah yang lebih jauh di tengah peta kepenyairan Malaysia.
END
Rabu, Januari 16, 2013
HORMAT
SAYA sudah lama sedar dan tahu betapa tidak ada gunanya sama sekali mencari penghormatan di kalangan sesama manusia. Selagi bernama manusia, walau betapa pun terpandang dan tingginya dia, apakah kerana pangkat, kuasa, harta dan kedudukannya, tetapi dia tidaklah atau bukanlah penentu hidup atau mati, atau bakal menentukan memberikan rezeki atau tidak kepada saya.
Sebagai insan Muslim, kiblat dan tempat menyembah saya bukanlah kepada mereka yang sesama manusia. Tempat saya meminta segala sesuatu dan mengharapkan diberikan penghormatan yang sepatut dan sewajarnya buat saya, setimpal dengan segala amal dan bakti saya, hanyalah kepada Allah SWT semata-mata.
Saya tahu, di mata Allah SWT martabat manusia itu tetaplah sama di antara sesama manusia. Yang meninggikan dia hanyalah amal ibadah, kepasrahan, sikap tawadduk, rendah diri dan hati serta kedermawanannya dalam semua hal. Selain itu tidaklah apa-apa untuk dijadikan tolok ukur atau perbandingan.
Kerana sedar dan tahu itu jugalah maka saya tidak pernah berasa terlalu tergiur untuk mendapatkan hormat dan kehormatan dari mana-mana pihak atau sesama manusia sehingga demi untuk mendapatkan itu saya perlu menjadi penjilat, pengampu dan pengemis kepada demi segala hormat dan kehormatan yang diidam-idamkan.
Kerana tidak terlalu tergiur terhadap segala hormat dan kehormatan yang tidak begitu perlu itu jugalah maka saya tetap dan selalu dengan hati terbuka ingin mengakui segala kelemahan serta kebodohan diri saya sendiri, tanpa perlu menopengkan segalanya dengan dusta dan sandiwara.
Ketika itu jugalah, ketika di dalam seni dan sastera orang berebut-rebutkan rasa hormat dan penghormatan itu dengan pelbagai cara, untuk digelar serta dikenal sebagai tokoh anu atau ini, walau pada hakikatnya tidak terlalu banyak tahunya, saya tetap memilih untuk hanya berdiri di sudut atau berada di pinggir menjadi pencatat yang setia dan rajin di dunia saya sendiri.
Biarlah mereka berebutkan rasa hormat dan pengormatan itui. Buat saya itu tidak perlu dan saya tidak ingin mencampuri mereka yang demikian kerana saya tahu segalanya bakal tidak membawa mereka ke mana-mana hanya dengan gelar dan ketokohan yang ringan dan kosong begitu. Kerana tidak pernah meninggalkan sebarang bekas dan jejak dalam bentuk karya yang walau setidak-tidaknya, setelah mereka pergi, mereka pasti sahaja tidak akan terus dikenang atau hilang ditimbusi debu masa silam.
Mereka selalu lupa akan kenyataan sastera dan seni yang jelas tetapi kejam: binalah karya dengan seluruh kekuatan jiwa dan bukan hanya dengan aksi dan omongan yang kosong.
Saya sedar dan tahu di luar sana mereka sedang berebut-rebutkan gelar itu. Ingin dipandang dan terpandang sebagai tokoh dalam segala genre dan bidang: penyair, penyajak, deklamator, sarjana. Walau sebahagian besarnya hanya berandalkan angin, ampu dan penjilatan.
Tetapi saya tidak penah menggiurkan itu. Apa lagi untuk berharap dan meminta-minta sesuatu yang memang bukan hak saya.
Januari 16, 2013
Selasa, Januari 15, 2013
TAHUN BARU 2013
SAYA menyambut tahun baru 2013 hanya dengan diam ketika berada di dalam pesawat udara yang sedang akan mendarat di bandara KLIA. Tanpa pekik, azam dan doa muluk dari bibir saya, tahun baru 2013 tetap datang dan hadir seperti apa adanya juga.
Dari KLIA, saya memasuki bandaraya Kuala Lumpur dengan bas yang menurunkan penumpang di depan bangunan Cahaya Suria. Saki baki pesta masih kelihatan berbekas dan saya menjadi terperanggah beberapa detik lamanya tatkala tengah malam di Kuala Lumpur di depan saya, diasak dengan teriak dan pekik suara bertelor Indonesia oleh segerombolan pemuda dan kemudian melihat gerombolan wajah-wajah Bangla, Myanmar, Nepal dan Vietnam di jalanan.
Apakah saya telah tersesat ke negara lainkah malam ini? Tanya terbetik di dalam hati saya sendiri. Sambil melihat lagak dan laku mereka yang berteriak tanpa segan dan silu dengan hati sebal. Tentunya juga saya tidak ingin menegur atau mengambil peduli mereka kerana sudah dapat menduga apa akan kesudahannya. Walau hati berasa terbakar dan seolah-olah menjadi kecil dan asing di negeri saya sendiri.
Saya tidak membenci atau kurang menyenangi kerana telor Indonesia, wajah Bangla, Vietnam atau Nepal mereka. Mereka berhak hidup dan bernafas walau di mana pun mereka berada. Apa lagi bila mana mereka didatangkan oleh para majikan dan taukeh yang mahu mengaut untung lebih dengan mengupah dan mengambil mereka sebagai tenaga kerja dengan upah yang lebih rendah, sehingga kadang-kala menjadi mangsa eksploitasi yang sangat tidak adil, mereka saya kira memang wajar untuk sekejap malam itu melepaskan perasaan sempena sambutan malam tahun baru itu.
Tetapi selepas itu apa? Saya hanya bertanya kepada diri sendiri mengenai ini: ketika kita bertempik bagaikan hendak putus urat leher mengenai ketuanan dan hak atas nama bangsa, kita sebenarnya sedang mempertaruhkan apa, atau hanya meneruskan sebuah sandiwara yang bakal tidak akan bertemu penyudahnya?
Kecuali setelah kita semakin kehilangan dan melepaskan terlalu banyak benda dan perkara semata-mata demi menjaga kerusi dan secuil kuasa milik peribadi.
Ketika laung ketuanan menjadi sindir dan perli yang sangat menyakitkan hati dan negeri milik kita semakin disesaki wajah-wajah asing yang menuntut sesuatu yang dijanjikan oleh mereka yang berkepentingan sebelumnya.
Kita terpaksa berkongsi dengan sesuatu yang bukan pun haknya dan laung ketuanan itu semakin lantang dikumandangkan.
Telinga kita semakin perit mendengarnya. Semakin lama. Semakin lama.
Bakal menjadi pekak dan tuli.
Januari 1, 2013
Khamis, Januari 03, 2013
PELARAM
SAYANG sekali. Dia kelihatan rajin dan agak teliti membaca. Tentunya tidak hanya buku sastera negaranya tetapi terutamanya juga buku-buku sastera dari luar negara. Memang kelihatan dia agak terlalu banyak tahu mengenai sesuatu yang dari luar: isu-isu, tokoh, peristiwa dan pemikiran sebahagian besar daripada bacaannya.
Namun sayang sekali. Dalam keagakan banyak tahunya itu dia seperti menjadi kesurupan dan hampir lupa untuk menimbulkan jejak peribadinya sendiri. Dia tenggelam dalam keseronokan membaca dan kembali bercerita mengenai segala sesuatu yang dia baca. Kadang timbul kesan dia hendak melaram-laramkan kepengetahuannya tanpa ditemui di mana pula dia berdiri sebagai peribadi yang membaca dan menzahirkan kesan serta persepsi bacaannya sendiri.
Sayang sekali. Dia sekadar mengulang-ulang kembali apa yang sudah dia baca dan bukannya mencerna dan menjernihkan di dalam akalnya sendiri, sesuatu yang pada akhirnya akan mampu menimbulkan sosok dan pandangan pemikirannya sendiri, yang khas milik dia selaku peribadi yang tersendiri.
Begitulah kulihat dan mengertikan. Dia ingin menjadi Camus, Marquez, Soyenka, Borge atau siapa sahaja yang telah dia baca dan hayati karyanya daripada bacaan-bacaannya.
Tetapi dirinya? Di mana dia letakkan ketika kembali dengan megah dan sombong dia mempamerkan apa yang sudah dan telah dia baca itu?
Sayang kerana kulihat dia seperti sengaja tidak mahu sedar atau memang dengan rela untuk tidak menjadi dirinya sendiri.
Atau seperti burung beo yang mengulang-ulang. Tanpa sedikit rasa cerdik untuk kembali berdiri sebagai dirinya sendiri.
Mungkin dia memang memilih untuk hanya menjadi PELARAM dan bukan seorang pencerna yang sekaligus befikir.
Januari 3, 2012
Langgan:
Catatan (Atom)